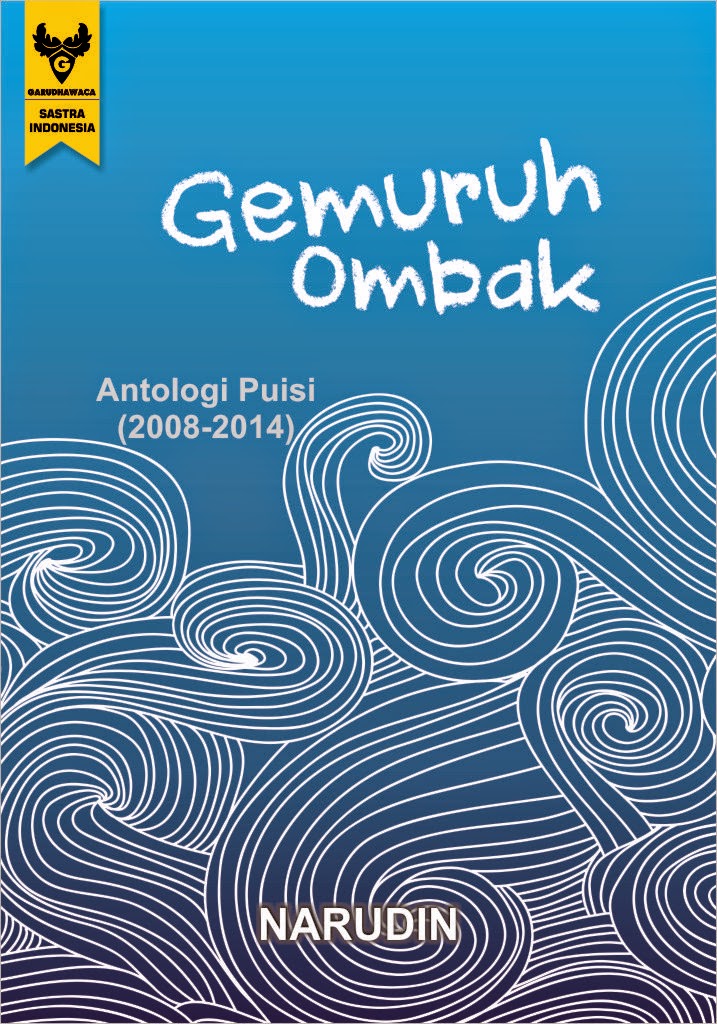Di jurnal Kalam Edisi 9 Tahun 1997 halaman 63-66, Daniele Sallenave menuturkan situasi dan tantangan sastra dan kepenulisan di jaman dan era kita saat ini, yang memang tidaklah sama dengan abad-abad sebelumnya. Menurutnya, karya-karya sastra di jaman kita ini tengah bersaing dengan sebuah kenyataan “komodifikasi” dan “ekonomisasi” segala hal, yang bahkan seringkali karya-karya sastra pun terjebak hanya sebagai hiburan semata dan produk-produk budaya instan. Keprihatinan Daniele Sallenave itu, menurut saya, memang cukup beralasan. Kita, misalnya, apabila pergi atau mengunjungi toko-toko buku, hampir pasti akan menjumpai buku-buku pop yang berlabel bestsellers dan mengklaim diri mereka sebagai karya sastra.
Rupa-rupanya, dunia “kepenulisan” atau “kesusastraan” secara umum memang tak luput dari cengkeraman dan zeitgeist jaman kita saat ini, yang dalam istilah Jean Baudrillard dapatlah disebut sebagai era dan jaman citra. Seringkali yang menentukan “apa” dan “bagaimana” sebuah buku akan dihargai dan dinilai oleh para konsumen atau para pembeli adalah labelnya, seperti label bestsellers yang telah dikatakan itu, bukan isi atau apa yang hendak dituturkan dan dinarasikannya kepada kita. Dengan kata lain, kita tak bisa luput dari realitas di mana iklan dan reklame telah merambah segala hal, termasuk dalam kadar penerbitan dan percetakan buku-buku yang mengklaim sebagai buku-buku sastra.
Bahaya yang tak kalah memprihatinkan, lanjut Sallenave adalah juga ketika sastra, tentu juga seni, hanya menjadi propaganda semata, sekedar menjadi alat hal-hal atau apa saja yang di luar sastra dan seni. Situasi-situasi, tantangan, atau bahkan gempuran kenyataan di jaman kita saat ini tak teringkari lagi memang ketika dunia sastra harus bersaing dengan dunia dan kenyataan ekonomisasi dan komodifikasi, yang seperti sama-sama kita rasakan dan kita ketahui, telah hampir menyentuh semua hal dalam hidup kita. Kita hidup di jaman ketika sastra harus bersaing dengan teknosains dan hasrat konsumeristik masyarakat jaman kontemporer, yang senantiasa ingin selalu membeli dan melarap segala hal yang instan.
Kenyataan itu juga, yang mau tak mau, dihadapi penyair di jaman ini: menulis di era ekonomisasi dan komodifikasi. Pilihannya terserah masing-masing penyair, merayakannya atau melarikan diri atau “menyelamatkan” diri darinya. Namun, barangkali saja, kita juga dapat menemukan peluang kompromi dan kesempatan baru bagi ilham dan kreativitas, tergantung kecakapan dan kemahirannya untuk bersiasat, menggali kemungkinan, atau bahkan menemukan hal-hal yang tak terduga, seperti halnya Walt Whitman yang begitu riang merayakan jaman mesin dan menyanyikan raungan lokomotif di era dirinya menulis puisi. Barangkali juga di jaman ini kita dipaksa untuk berendah-hati atau tidak berambisi untuk menulis puisi yang ajaib, dan cukup “memindahkan” pengalaman atau perenungan bathin dan intelektual pribadi penyairnya dengan santai dan remeh.
Kita pun sama-sama tahu, dalam skala luas dan di luar konteks perbincangan seputar puisi dan tantangan “penulisannya” ini, di jaman ini, rezim pasar nyaris paripurna menguasai segala lini dan sisi kehidupan. Tak terkecuali agama yang telah menjadi alat untuk kepentingan sekular paling vulgar. Lihat saja, presiden partai yang partainya mengklaim sebagai partai Islam, tersungkur di jeruji penjara karena kasus korupsi. Bahkan, di jaman ini, Tuhan dan agama pun dikomoditaskan, justru dengan sangat gamblang, ketika hampir dari kita semua seakan tak sanggup lagi mengelak dari tirani pasar. Singkatnya, apa yang diutarakan Sallenave itu memang bukan isapan jempol semata.
Dunia, Sajak, Ruang
Dalam kasus beberapa puisi Narudin, semisal puisinya yang berjudul Percakapan Ke-0, yang terpancar dan terasa kepada saya adalah pergulatan dan meditasi “aku” dalam sebuah kosmik atau jaman di mana diri dan individu seakan merasa terancam, bahkan seperti tak berdaya ketika berhadapan dengan waktu, ruang, dan situasi jaman, dalam sebuah dunia di mana sajak dan penyairnya berada: “Di ruang ini, aku menunggu diriku yang belum kembali; di ruang itu, kau menunggu dirimu yang telah kembali. Di waktu ini, aku menghitung waktu sebelum lahir dan setelah mati”. Dalam puisi tersebut, pertanyaan dan investigasi seputar waktu dan ruang begitu dominan, yang mengingatkan saya pada meditasi filosofisnya Martin Heidegger menyangkut isu yang sama: seputar “Ada”, yang juga dengan sendirinya menyangkut waktu dan ruang,
“Apa maksud ruangku di sini (pun di sana?), dan waktuku di sana-sini?
Adakah Sesuatu di luar semesta alam yang tak terikat “waktu” dan “ruang” ini?
Apakah Yang menyiksa di keabadian (kelak, pasti) merasa menyesali?
Biarlah si burung hantu buta itu mencari hati dalam gelap tak terperi,
biarlah si burung hantu buta itu mengebumikan sunyi yang ter-cederai!
Siapa di antara kita, burung yang bicara ter-lantang, dan pandai terbang?
Sayap ini masih bagai punuk unta di dada, kelak bukan atas kehendak dirinya melayang?
“Tapi, ke mana? Di mana? Kapan?” gelisahmu meremang.
“Apa pula hakikat waktu dan ruang, hai kau, Sayang!”
Bisakah kuhapus si waktu dan si ruang itu dengan setetes air mata berlinang?
Atau tubuh dan ruh, mesti salah satu dibuang?
Di ketinggian, bukan, si burung hantu buta menemukan Bayang cemerlang?
Lalu, ke mana segala kenangan manis ini hendak mengendap, Tersayang?
Di dalam getir kematian atau ketiadaan yang berulang?
Mengitari seluruh galaksi alam ini, tamasya buta: semesta batin nan luas benarkah terlampaui?
Menerka kenapa siang tetap menyilaukan, dan malam terus menghangati. Nanti begini?
Keluhmu, “Hentikan semua permainan ini!”
“Ada-kah permainan yang selalu menyenangkan hati?”
Segera, pergilah,
aku tetap di sini:
giliran siapakah?
Tak usah ditafakuri.”
Untuk memahaminya, tentu sebagai perbandingan saya dalam membacanya, ada esai menarik yang ditulis Michelle Yeh (Oto-Puisi, Rumah Lebah Jogjakarta 2012, hal. 196-2013) tentang sejumlah penyair Avant-Garde China yang mayoritas mengalami kesepian dan kemalangan dalam hidup mereka, beberapa bahkan melakukan bunuh diri di usia muda. Para penyair yang menolak menjadi alat partai itu memilih kesepian dan pengembaraan, menjadi para santo, dengan penuh keberanian dan spirit pemberontakan, beberapa di antara mereka hidup menggelandang, menjadi para raja di singgasana kesunyian mereka masing-masing. Tak lain karena mereka menghendaki seni dan puisi mereka terbebas dari “penaklukkan” oleh kepentingan dan tekanan-tekanan dari luar “hasrat puitik” yang bebas. Contohnya tercermin dari kredo-puitik Cai Hengping yang menyatakan bahwa hal itu demi menjaga “warisan kita yang tersisa”, yang ironisnya, tak ubahnya “menjaga berlian surgawi dalam puncak kemelaratan” serta “menikmati kerajaan dan kemuliaannya”. Meski kredo tersebut terdengar bernada romantik, barangkali memang didasari atas kehendak untuk tidak takluk kepada serangan banalitas jaman, yang seperti dikemukakan awal tulisan ini, juga menjadi keprihatinan Daniele Sallenave, seputar sastra di tengah tantangan jaman konsumeris dan dalam sebuah dunia di mana tirani pasar seakan mencengkeram semua sisi dan sudut kehidupan kita saat ini.
Persis dalam konteks yang demikianlah, puisi Narudin berjudul Percakapan Ke-0 itu, menurut saya, mendapatkan relevansi meditatifnya sebagai sebuah gugatan sekaligus sebagai refleksi dan perenungan. Puisi itu menurut saya dapat dikatakan mewakili sebagai suara-suara yang berusaha memeriksa kembali keberadaan kita sendiri di jaman ini sebagai manusia dan individu, di mana nada investigatif-nya berusaha menohok ke jantung subjek kita sendiri untuk berani bertanya dan mempertanyakan situasi dan ruang jaman kita. Sedangkan secara retoris, nada dan suara puisi Narudin berjudul Percakapan Ke-0 itu, tak ubahnya deklarasi Jing Ke, sang pendekar abad ke-4 sebelum masehi, justru di saat ia sadar bahwa dirinya tengah berhadapan dengan badai dan tirani sang raja lalim Qin, ia harus mengambil resiko demi menemukan kebebasan dan jatidiri seorang pendekar: “Aku menjalin cinta rahasia dengan keabadian, dan misteri pilihan kupahami sebagai perkara ada dan ketiadaan”.
Puisi dan Waktu
Seperti dapat dibaca oleh kita, selain meditasi diri di dalam dan berhadapan dengan ruang, puisi Percakapan Ke-0 itu juga merefleksikan meditasi tentang waktu, atau tepatnya meditasi diri di dalam dan berhapan dengan waktu: “Siapa di antara kita, burung yang bicara ter-lantang, dan pandai terbang? Sayap ini masih bagai punuk unta di dada, kelak bukan atas kehendak dirinya melayang? “Tapi, ke mana? Di mana? Kapan?” gelisahmu meremang. “Apa pula hakikat waktu dan ruang, hai kau, Sayang!” Bisakah kuhapus si waktu dan si ruang itu dengan setetes air mata berlinang?” Meditasi tentang waktu dalam sajak tersebut berusaha menohok dan sangat investigatif, barangkali mencoba mendefinisikan kembali apa yang kita pahami tentang waktu, utamanya di jaman citra dan komodifikasi, di jaman mesin dan hingar-bingar industri saat ini, di mana waktu dipahami dan diakrabi secara mekanik dan terukur dengan menggunakan alat penunjuk waktu, semisal jam. Di sisi lain, kita tahu bahwa pemahaman waktu seperti itu terbilang banal, dan karenanya ada banyak definisi dan pemahaman waktu yang berbeda bagi para filsuf, santa, dan para penyair: durasi, keabadian, pengalaman batin menyangkut “keberuangan”, dan “kematian”, seperti yang dikemukakan Martin Heidegger, Henry Bergson, Teilhard De Chardin dan lain sebagainya.
Investigasi ruang dan waktu dalam beberapa puisi Narudin itu cukup menggoda kita untuk merenungi diri kita sendiri sebagai bagian dari kosmos, bahkan dalam keberhadapan kita dengan kosmos dan dunia di mana kita hidup dan berada, sebagaimana tercermin juga dalam puisinya yang berjudul Manusia Mujarad: “Sekawanan manusia memadati jalanan bagai kabut-kabut ruh azali, menggembalakan angan-angan, ternak-ternak masa depan. Sekawanan manusia
memenuhi ruang mujarad, demi sesuap nasi, sebotol susu atau sebotol minuman, demi anak haram, demi mimpi-mimpi agung tersembelih. Sekawanan manusia digiring masuk pabrik atau kandang, diolah menjadi barang-barang, dikunyah, dimuntahkan, menjelma kotoran”. Bahkan penyairnya sendiri seakan hendak menegaskan bahwa penyair menulis puisi-puisinya dalam konteks ruang dan waktu tersebut, bahwa menulis itu sendiri hanya dimungkinkan oleh interaksi yang intens dengan kesekitaran kita, dan bahwa puisi lahir dari hubungan kita dengan ruang dan waktu, dengan kosmos dan dunia keseharian kita: “Penyair tak pernah menulis puisi dengan tangan” (Penyair).
Di sini, ijinkan saya memaparkan perspektif saya sendiri tentang ruang dan waktu, yang akan saya kiaskan dengan Desa dan Kota, di mana pengalaman saya tentang desa dan kota membekaskan durasi dan intensitas yang berbeda. Desa adalah kenangan dan ingatan kanak-kanak dan remaja saya. Waktu yang tak beranjak. Sedangkan kota adalah persinggahan dan pelarian saya sebagai seorang lelaki, menjumpai kegelisahan dan agresivitas hidup yang mengagumkan sekaligus mencemaskan. Kedua situasi tersebut pada akhirnya memberikan ketegangan pemahaman saya tentang waktu. Di desa, waktu seakan diam merenung, kegelisahannya mungkin lebih karena saat ia terbangun dari tidurnya, ia juga tak luput dari rasa bosan. Dan ketika ia terjaga, ia mengangankan dirinya sebagai keabadian. Tetapi waktu yang resah ketika saya hidup di kota, menemukan kedamaiannya ketika saya memandangi hamparan merah senja dari balik kaca jendela gedung bertingkat. Pada saat itu, lalulintas dan lalulang di bawahnya saya bayangkan sebagai jelmaan langkah-langkahnya menuju kepulangan ke tempat di mana ia ingin beristirahat. Di desa, saya akan membayangkan waktu tak ubahnya sebuah sungai. Tetapi di kota, saya akan membayangkannya sebagai barisan lampu-lampu jalan.
Ketegangan dan intensitas pemahaman seperti itu akan menorehkan corak dan suara-suara yang berbeda ke dalam sajak. Dalam konteks ini, sebuah sajak mengimajinasikan dirinya setelah mempersepsi dan mengkiaskan benda-benda dan realitas yang dijumpai dan dialaminya. Pada garis ini, proses penulisan sebuah sajak adalah interaksi dan ketegangan antara kenyataan benda-benda dan pemahaman yang menginginkan dirinya bersama benda-benda dan kenyataan untuk kemudian ditangkap pemahaman dan suara yang berbeda demi menimbulkan efek dan dampak musikal bagi terciptanya kuriositas dan wawasan yang baru. Persis bersama itulah, kata-kata dan bahasa mesti digubah menjadi musik dan suasana yang adalah kiasan sebuah sajak.
Percaya pada garis wawasan seperti itulah, bagi saya kekuatan sebuah sajak pertama-tama dapat saya rasakan pada sejauh mana suara-suara dan nada-nada yang dikumandangkannya sanggup mengajak saya berbincang akrab, yang dapat membuat saya ingin terus mendengarkan apa yang tengah dikisahkannya dan apa yang dinyanyikannya, hingga ketika saya membaca sebuah sajak, sajak yang saya baca itu terus meminta untuk ikut bersamanya, menyelami dunia-dunia yang tengah ia lagukan. Tak penting apakah kemudian saya dapat memahami atau menangkap maknanya ataukah tidak. Sebab kekuatan sebuah sajak bagi saya justru ketika ia membuat saya tersesat dan tenggelam begitu saja ketika membacanya, yang dengannya saya berendam dalam keindahannya.
Dengan puisi, kesetiaan kita terletak pada sikap kita untuk terus-menerus meragukan dan mempertanyakan pemahaman dan wawasan kita. Karena yang nyata adalah benda-benda dan kenyataan hidup itu sendiri, di mana dengannya pemahaman dan wawasan kita adalah sebentuk afirmasi pada hidup dan kefanaan yang acapkali memberikan pengecualian, kejutan, dan kebetulan yang seringkali tak kita duga. Ia seperti musik yang hanya membawa kita pada alam dan realitas pengembaraan dan pencarian yang sinambung dan rendah hati, bukan memposisikan diri memberi jawaban yang hanya akan berujung pada dogma.
Persis karena demikianlah, seorang penyair adalah seorang penanya dan filsuf, bukan seorang ilmuwan politik.
Yah, musik dan benda-benda berperan besar dalam proses pembentukan terus-menerus sebuah sajak. Musik lah yang dapat saya anggap sebagai bahasa purba, bukan kata-kata. Kata-kata hanya medium dan salinannya. Adakalanya ia mewujud dalam durasi dan intensitas yang lambat, dan kadang cepat meninggi, tangkas, spontan tak terduga. Puisi adalah seni yang tak hendak melakukan peniruan seperti yang didogmakan Plato, tetapi lebih sebagai prosesi musikal dan pengembaraan nada-nada, di mana yang dapat kita sebut sebagai kiasan atau allegory adalah suasana yang dibangun oleh nada-nada itu sendiri.
Demikianlah, menurut saya, komitmen kepenyairan adalah komitmen pada yang profan, sebagaimana yang didendangkan oleh Rubayyatnya Abu Sa’id dari Khorasan: “Ketika aku seekor singa, harimau adalah mangsaku. Aku menangkap segala yang kuburu. Ketika aku hendak memeluk erat-erat cintaMu, seekor rubah pincang mengusikku dari liangku”. Komitmen pada yang profan itulah yang akan terus mengasah bahasa dan kepekaan musikal seorang penyair, yang dengan demikian, seorang penyair memang lebih baik menjadi orang yang biasa dalam arti seseorang yang terus-menerus membangun kemampuan penangkapan pancaindera dan kepekaan bathinnya pada kefanaan, yang dapat melahirkan suara-suara kejujuran dan terbebas dari hasrat untuk mengkonseptualisasi kenyataan dan benda-benda ala seorang ilmuwan atau pengamat politik.
Dan sekarang, ijinkanlah saya menutup tulisan singkat saya ini dengan penggalan puisi Narudin yang berjudul Kabar, yang menurut saya dapat mewakili perspektif saya sendiri tentang puisi yang memiliki unsur musikal dan meditatif yang lembut dan santai, yang dengannya puisi menjalankan modus berpikir alternatif sembari tetap memberi hiburan dan kesenangan, menjadi seni itu sendiri, kepada kita sebagai pembaca dan penyimaknya, “Langit mengabari bumi bahwa hari hendak hujan. Tapi, angin meniup arak-arakan awan kelam itu perlahan-lahan. Dan laut tersenyum, menanti curah hujan itu, walaupun ombak-ombak membuat senandung gaduh. Ada yang tertegun di kaki langit pincang itu. Ia berjalan mendekatiku membawa kabar dari negeri jauh”. Selamat membaca!
Sulaiman Djaya (Esai ini merupakan pengantar untuk buku puisi Gemuruh Ombak karya Narudin yang diterbitkan Garudhawaca 2014 dan dapat dibaca di halaman 7-14 buku tersebut)